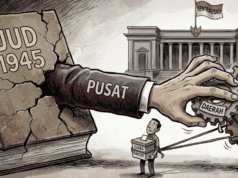Saya tidak sedang ikut campur. Saya hanya kecipratan, seperti seseorang yang kebetulan lewat di tengah jalan basah, lalu terkena cipratan kendaraan yang melaju cepat. Sebuah percakapan menyeruak di antara segelas kopi dan sebatang rokok, tentang sesuatu yang bagi sebagian orang dianggap sakral: nasab. Percakapan itu bukan milik saya, tetapi ia menyelinap masuk, menjadi bagian dari yang tak bisa dihindari. Setidaknya untuk saat ini.
Dan seperti kebanyakan percakapan yang berlapis tradisi, ia tak selesai hanya dengan tawa kecil atau anggukan sepakat. Ia tumbuh menjadi perdebatan panjang, menggali yang lama terkubur, menyeret yang baru ke panggung pertanyaan. Saya tak tahu siapa yang benar, tetapi cerita ini terus berputar, seperti arus yang tak mengenal muara.
Nasab adalah perkara pelik. Di sanalah identitas bertemu kebanggaan, di mana darah mengalir bersama sejarah, sekaligus beban yang dipikul. Dalam tradisi Islam, kata nasab tak hanya mencatat dari mana seseorang berasal, tetapi juga ke mana ia diharapkan menuju. Namun, dalam kasus Ba’alawi—kelompok keturunan Nabi Muhammad SAW yang berasal dari Hadhramaut, Yaman—nasab menjadi arena perdebatan panjang, seperti meniti benang halus antara iman dan fakta.
Kisah ini bermula di abad ke-12, ketika Sayyid Ahmad al-Muhajir meninggalkan Basrah, Irak, menuju Hadhramaut. Ia adalah leluhur Ba’alawi, garis keturunan yang diyakini bersambung langsung kepada Rasulullah. Mereka berdakwah, berdagang, dan menyebar hingga ke Nusantara. Tapi, seperti sebuah dongeng, cerita ini tak hanya dihuni oleh kebanggaan, melainkan juga keraguan.
Di Indonesia, Ba’alawi dihormati. Mereka bukan hanya tokoh agama, tetapi juga simbol moralitas. Gelar habib yang mereka sandang menjadi jubah yang diharapkan melambangkan keutamaan akhlak. Namun, di balik hormat itu, ada yang terusik: apakah benar semua ini bermuara pada Nabi? Atau ini hanya dongeng yang diceritakan berulang hingga dianggap nyata?
KH Imaduddin Utsman al-Bantani menantang dongeng itu. Dalam bukunya, Membongkar Skandal Ilmiyah Genealogis & Sejarah Ba’alawi, ia menelusuri keabsahan klaim nasab Ba’alawi. Baginya, ini bukan sekadar masalah identitas, tetapi soal kejujuran intelektual. Dengan tajam, ia menunjukkan celah dalam silsilah yang selama ini diterima tanpa banyak tanya. Ada interpolasi, manipulasi, dan kesenjangan sejarah yang tak terjawab.
Ahmad Muhajir dan Afra Alatas, dalam The Debate on the Ba‘Alawi Lineage in Indonesia, mengambil langkah serupa. Mereka menyisir kembali sejarah dan menemukan bahwa genealogi ini, meskipun diterima oleh banyak ulama, tidak selalu tahan uji. Tapi, apakah ini soal mencari kebenaran, atau sekadar membongkar mitos?
Di sisi lain, gelombang pembelaan juga deras. Syekh Ali Jum’ah, mantan Mufti Mesir, menyebut bahwa nasab Ba’alawi telah diterima sebagai ijma’ ulama sepanjang sejarah. Namun, persoalan tak berhenti di garis nasab. Ada kritik yang lebih personal: eksklusivitas. Tradisi kafa’ah, yang mengharuskan Ba’alawi menikah sesama kelompok, dianggap menciptakan jurang sosial. Apakah ini upaya menjaga kemurnian, atau justru pembatasan yang menyalahi esensi Islam yang universal? Bagi sebagian, takwa lebih utama dari darah. Bagi yang lain, ini adalah warisan yang tak boleh luntur.
Lalu, di mana kita berdiri?
Literasi media memperumit segalanya. Informasi yang beredar di dunia digital mempercepat opini terbentuk, sering kali tanpa verifikasi. Jurnal Media Literacy and Differences in Scholars’ Views on Nasab Ba’alawi menunjukkan bagaimana masyarakat terbelah antara penghormatan tradisi dan dorongan untuk mengkritisi. Ada yang menganggap nasab ini sebagai cahaya yang tak boleh padam; ada pula yang merasa perlu menyalakan lampu agar mitos tak menutupi kebenaran.
Di balik semua ini, peran Ba’alawi dalam sejarah Nusantara tetap tak terbantahkan. Mereka adalah pelopor dakwah, pendiri pesantren, dan penjaga tasawuf. Itu yang tertulis dalam jurnal The Contribution of Alawiyyin Scholars in Grounding Islam in the Archipelago. Sang penulis, Dzulkifli Hadi Imawan, menggarisbawahi bagaimana Ba’alawi membawa Islam ke pelosok Nusantara dengan kelembutan, mendirikan lembaga pendidikan, dan mengharmoniskan dakwah dengan budaya lokal. Tapi, apakah kita akan selalu memaafkan sejarah hanya karena kontribusinya?
Genealogi, pada akhirnya, adalah persoalan manusia. Sejarah adalah catatan yang selalu bisa ditulis ulang, baik oleh penguasa, ulama, atau oleh waktu. Kita berdiri di antara dua kutub: penghormatan pada tradisi dan kebutuhan untuk jujur pada fakta. Di tengah itu, ada nasab yang dipikul seperti tongkat estafet. Apakah tongkat itu mengarah ke kebenaran atau sekadar ilusi, barangkali hanya waktu yang bisa menjawabnya.
Tetapi, lebih dari sekadar itu, pertanyaan tentang nasab adalah refleksi tentang siapa kita, bukan hanya dari mana kita berasal. Apakah garis keturunan hanya soal darah yang diwariskan, ataukah ia adalah cerita panjang tentang nilai, akhlak, dan perbuatan yang membentuk siapa kita hari ini? Apakah nasab adalah kebanggaan yang harus dijunjung, ataukah ia hanyalah penanda di tengah perjalanan hidup yang jauh lebih luas dari sekadar asal-usul? Kita tak pernah tahu pasti. Karena pada akhirnya, kita hanya bisa bertanya—dan pertanyaan itu menggantung di udara, menunggu untuk dijawab, bukan oleh siapa pun, melainkan oleh diri kita sendiri.
Nurhidayat
Jagakarsa, 16 Desember 2024