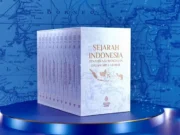Mataram, seperti kebanyakan kota-kota lain, tak pernah benar-benar sepi. Di Kota ini juga ada pedagang asongan. Tetapi tak menjual es teh. Ia menyodorkan sebungkus kacang. Tangannya kurus, jemarinya hitam, senyunnya lebar. “Kacang ini lebih gurih dari cerita hidup saya,” katanya
Pedagang asongan. Mereka ada seperti bayang-bayang: tak menuntut terlihat, tak meminta dipahami. Mereka tidak berbicara tentang ekonomi sebagai teori atau kapitalisme sebagai musuh. Mereka adalah ekonomi itu sendiri—berjalan di bawah matahari, dari trotoar ke trotoar, dari stasiun ke stasiun, seperti arus kecil yang mengalir di antara batu-batu besar.
Apa yang mereka bawa sederhana: botol air, rokok, permen, tisu basah. Barang-barang kecil yang mungkin hanya dicatat sebagai angka sepele dalam statistik kota. Tapi mereka ada, menempati ruang yang tak pernah diisi toko besar, tak pernah dijangkau birokrasi. Kehadiran mereka adalah jeda di tengah maraknya gedung-gedung tinggi, sebuah pengingat bahwa tidak semua yang bergerak di kota ini mencolok dan bersuara keras.
Namun apa yang kita berikan kepada mereka? Kadang kita tersenyum, lebih sering kita lupa. Kadang ada lelucon yang dilemparkan, ringan seperti nasib mereka. Tapi siapa yang benar-benar tertawa? Pedagang itu? Tidak. Mungkin kota ini, yang selalu melangkahi mereka tanpa merasa kehilangan apa-apa.
Pedagang asongan, seperti sejarah, adalah saksi bisu dari perubahan zaman. Di Vietnam, di Tiongkok, di Indonesia—mereka ada, tapi tidak pernah benar-benar hadir dalam pembicaraan serius. Sebuah jurnal internasional, misalnya, menceritakan bagaimana pedagang di Hanoi harus melawan kebijakan kota yang ingin “membersihkan” mereka dari trotoar. Di Tiongkok, pedagang kecil sering kali dianggap ancaman bagi estetika modernitas. Mereka diusir, direlokasi, atau dilupakan.
Tapi bisakah kita benar-benar “membersihkan” mereka? Kota tanpa pedagang asongan adalah kota yang lupa bahwa manusia hidup tidak hanya dari gedung pencakar langit, tetapi juga dari segelas teh manis yang dijual di sudut jalan. Pedagang asongan adalah pengingat: bahwa di balik setiap kemewahan, ada yang sederhana; di balik setiap kemajuan, ada yang tertinggal.
Namun, apakah mereka hanya akan menjadi pengingat? Atau kita bisa lebih dari itu? Sebuah negara yang menghargai kerja keras harusnya memberikan ruang bagi mereka. Tidak sekadar ruang fisik, tetapi ruang untuk bermartabat. Tidak lagi melihat mereka sebagai gangguan, tetapi sebagai bagian dari kehidupan itu sendiri..
Kita sering lupa bahwa hidup kita ditopang oleh banyak tangan yang tak terlihat. Sebuah bungkus kacang di kereta, segelas teh manis di pinggir jalan, sebuah senyuman kecil yang tulus—semua itu adalah pengingat bahwa di balik setiap kesibukan kita, ada mereka yang bekerja lebih keras, lebih lama, dan lebih dalam diam.
Kita, yang mungkin lebih beruntung, harus bertanya: apa yang bisa kita lakukan untuk mereka? Atau, setidaknya, bagaimana kita bisa lebih baik dalam melihat mereka? Mungkin dimulai dari tidak mencemooh mereka. Mungkin dari memberikan sedikit ruang di trotoar, di hati, dan di cara kita memandang dunia. Pedagang asongan adalah bagian dari kota, dan kota tanpa mereka adalah kota yang kehilangan kemanusiaannya.
Nurhidayat | Mataram, 10 Desember 2024